Oleh: Ahmad Dairobi*
Memang sudah semestinya seorang Muslim punya keinginan agar umat Islam bersatu kembali di bawah satu pemimpin, seperti pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin juga Bani Umayah. Jika tidak, maka layak dipertanyakan komitmennya terhadap agama. Hal itu sebagai sebuah idealisme. Soal mungkinkah persatuan itu terwujud atau tidak, itu soal lain.
Barangkali semua Muslim sepakat bahwa pemerintahan ideal itu adalah pemerintahan khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin. Sehingga, khilafah banyak dianggap sebagai bentuk asli dari pemerintahan Islam, meskipun sebenarnya khilafah bukanlah sebuah bentuk, namun sebuah semangat.
Kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, jelas sekali bahwa khilafah itu bukanlah sebuah bentuk. Arti khilafah menurutnya adalah membawa masyarakat untuk mencapai kebaikan dunia-akhirat dengan mengikuti pola pikir Syariat. Definisi ini dibuat oleh Ibnu Khaldun untuk membedakan dengan al-mulk (kerajaan) yang berarti membawa masyarakat atas dasar kepentingan dan nafsu. Makna yang hampir sama disampaikan oleh Khudhari Bik dalam Itmâmul-Wafâ dan Abdul Wahhab an-Najjar dalam al-Khulafâ' ar-Râsyidûn.
Menurut beberapa Hadis, khilafah memang selesai pada tahun 40 Hijriah atau 30 tahun setelah Rasulullah r wafat. Namun, dalam Hadis lain, Rasulullah r masih menyebut para pemimpin setelah itu sebagai khalifah, semisal yang terdapat dalam Hadis tentang 12 khalifah yang diriwayatkan dari banyak jalur. Dengan demikian, maka yang dimaksud khilafah yang berakhir pada tahun 40 itu adalah khilafah yang ideal.
Secara umum, kamus politik internasional menyatakan bahwa khilafah berakhir pada tahun 1924 M, setelah runtuhnya Dinasti Utsmani di Turki. Kesimpulan ini didapat mungkin karena setelah Dinasti Utsmani tidak ada lagi negara Islam yang menyematkan label khilafah dalam pemerintahannya. Atau, mungkin karena Dinasti Utsmani merupakan negara Islam terakhir yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Atau, mungkin karena Dinasti Utsmani berdiri di Abad Pertengahan. Memang, hampir semua pemerintahan Islam yang muncul di Abad Pertengahan mengklaim dirinya sebagai "Khilafah".
Ibnu Khaldun memilih untuk tidak memastikan sampai abad berapa khilafah itu bertahan. Ketika melihat kecenderungan politik antar-masa, ia hanya membuat kesimpulan bahwa kadar kekentalan khilafah bisa dibagi tiga, yaitu khilafah murni, khilafah campuran, dan khilafah labelnya saja. Masa Khulafaur Rasyidin masih murni khilafah, karena pemerintahan betul-betul berdasarkan agama. Masa Umayah sampai masa-masa awal Abbasiyah, secara umum, landasan agama dalam khilafah sudah bercampur baur dengan politik kekuasaan yang dibangun di atas orientasi golongan dan kepentingan duniawi penguasa. Setelah itu, secara umum, khilafah sudah tinggal nama dan klaim, sedangkan esensinya sudah hilang sama sekali.
Maka, ketika kata "khilafah" diucapkan, cukup sulit bagi kita untuk menebak apa maksudnya. Sebab, persepsi orang tentang pengertian khilafah memang berbeda-beda.
Adapula yang cenderung memahami khilafah sebagai persatuan umat Islam di bawah satu pemimpin atau umat Islam hanya punya satu negara dan satu pemimpin. Mengikuti pengertian ini, maka khilafah secara umum berakhir pada masa Umayah. Setelah itu sudah bukan khilafah, karena Muslimin sudah terpecah ke dalam dua pemerintahan, lalu ke dalam beberapa negara.
*****
Apapun persepsi tentang khilafah, yang jelas semuanya merujuk pada masa Khulafaur Rasyidin. Hanya saja sudut pandangnya berbeda-beda.
Meski untuk kembali ke Khulafaur Rasyidin hampir mustahil, minimal kita wajib punya keinginan atau impian kembali ke
Kudeta Abbasiyah membuat Damaskus menjadi lautan darah. Rencana pemberontakan Sayidina Husain terhadap Yazid berakhir dengan tragedi
Karena pertimbangan risiko tinggi itu, ulama-ulama fikih nyaris menutup pintu untuk memberikan izin bagi terjadinya pemberontakan, kudeta dan semacamnya, meskipun penguasa yang hendak dihabisi adalah penguasa yang zalim.
Oleh karena itu, ulama-ulama fikih cenderung menyatakan sah terhadap pemerintahan-pemerintahan Muslimin yang tidak sesuai kriteria Syariat, baik yang tidak sesuai itu adalah kualitas pemimpinnya atau sistem pemerintahan yang dianutnya. Keputusan ini diambil karena realitas politik memang tidak memungkinkan untuk menerapkan semua kriteria secara utuh. Inilah yang disebut kondisi darurat. Dalam kondisi ini, berada di bawah pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada tidak memiliki pemimpin sama sekali. Memiliki pemerintahan yang tidak ideal masih lebih baik daripada terjadinya pertumpahan darah yang tak ada ujungnya.
Kalau kondisi tidak ideal itu selalu disikapi dengan upaya kudeta dan pemberontakan, maka umat Islam akan mengalami nasib yang sama dengan Khawarij. Dari satu rezim ke rezim yang lain, Khawarij selalu menjadi opisisi ekstrem dan berada di
Melihat berbagai ilustrasi di atas, inti yang ingin penulis sampaikan di sini adalah bahwa kita wajib punya impian untuk memiliki pemerintahan sebagaimana masa Khulafaur Rasyidin. Jika memungkinkan dan tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar, kita juga wajib berjuang untuk menegakkan dan menghidupkan kembali pemerintahan Khulafaur Rasyidin, baik dalam bagian-bagian tertentu atau (kalau bisa) secara utuh.
Namun demikian, pemerintahan kita saat ini tetaplah merupakan pemerintahan yang sah; undang-undang dan peraturannya yang tidak melanggar Syariat wajib kita patuhi. Dan, jika memungkinkan dan tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar, kita juga harus memperjuangkan agar negara ini bisa menjadi lebih sesuai lagi dengan Syariat dan mengupayakan agar umat Islam bisa bersatu kembali di bawah satu pimpinan.
Sekali lagi, semua itu, kalau memungkinkan dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.[]
* Penulis adalah Kepala Badan Pers Pesantren Pondok Pesantren Sidogiri dan Mantan Pemimpin Redaksi IJTIHAD periode 1421 H. Tulisan ini dimuat di Majalah Ijtihad Edisi 28


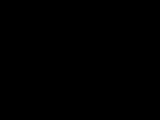
No comments:
Post a Comment